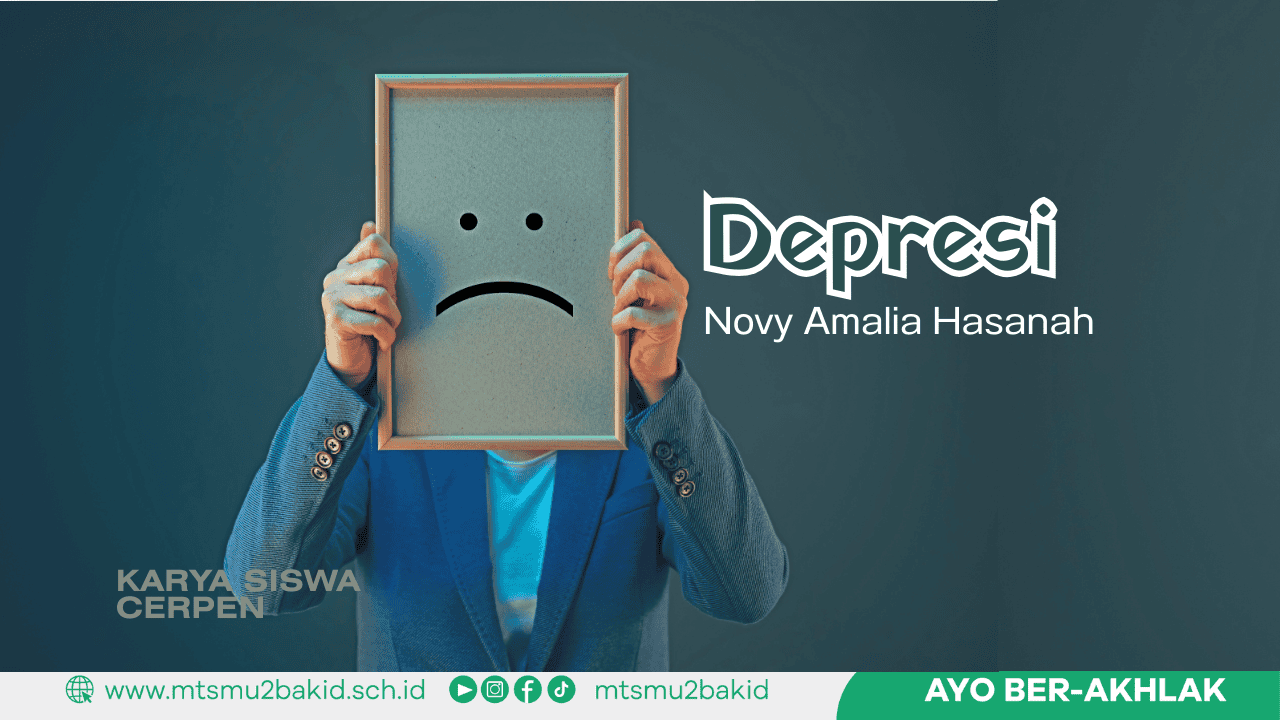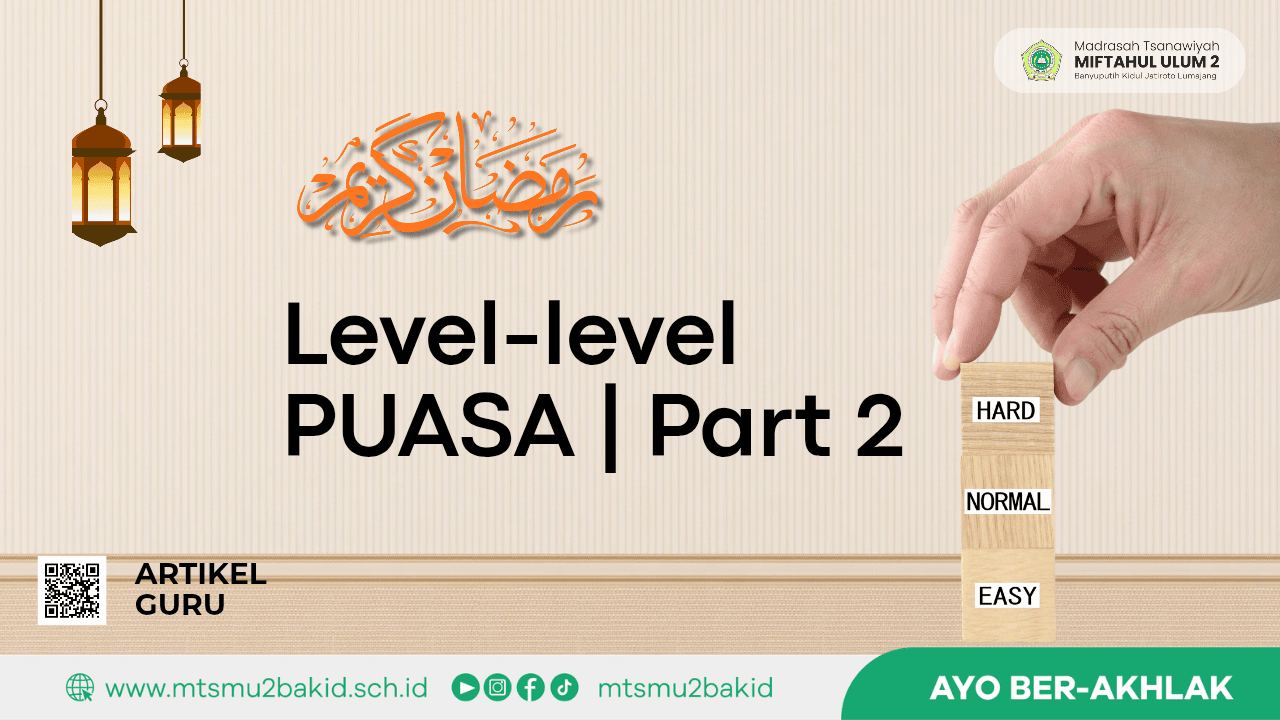Karya: Novy Amalia Hasanah *)
Pukul 00.00 adalah jam hantu bagi sebagian orang.
Ketakutan tanpa wujud menyelimuti pikiran, bayangan-bayangan liar berlarian tanpa arah.
Namun bagi seorang gadis bernama Chelsa, tengah malam justru adalah sahabat paling setia.
Di saat dunia terlelap, ia merasa hidup.
Kesunyian adalah rumahnya.
Tanpa tuntutan. Tanpa harapan orang lain. Tanpa perlu berpura-pura kuat.
Chelsa bukan penakut, tetapi juga bukan pemberani.
Pahlawan dalam hidupnya hanyalah orang tuanya.
Cinta tidak pernah ia anggap penting—baginya, memiliki satu teman sejati jauh lebih berharga daripada kisah romansa yang rapuh.
Sejak kecil, Chelsa terbiasa dilukai oleh sikap manusia.
Hari ini ia disapa, besok ia diabaikan.
Seminggu dianggap ada, sebulan diperlakukan seperti bayangan.
Ia tidak melawan. Tidak marah.
Ia hanya diam—berpura-pura tidak peduli, meski pikirannya terus bertanya,
“Apa yang salah denganku?”
Sekolah menjadi tempat paling melelahkan.
Yang ia inginkan hanyalah pulang, mengurung diri, dan mengumpulkan kembali sisa-sisa tenaganya—sendiri.
Bercerita hanya akan membuatnya dicap berlebihan.
Maka ia memilih memendam segalanya.
Waktu berlalu. Chelsa tumbuh.
Namun masa lalu tumbuh bersamanya.
Di bangku SMA, ia memutuskan berubah.
Ia tersenyum pada semua orang.
Tertawa keras.
Bercerita tanpa henti.
Ia mengenakan topeng ceria agar tidak terluka lagi.
Lalu datang Aura—
si cantik dengan syal merahnya.
Bersama Aura, kelas sunyi terasa hidup.
Cerita mengalir tanpa henti.
Namun Chelsa tetap menjaga jarak.
Ia takut—takut menganggap sesuatu istimewa, lalu kehilangannya lagi.
“Ra, lo nonton drama baru nggak?”
“Apaan.”
“My Demon. Seru banget.”
“Nggak.”
Jawaban Aura selalu singkat, dingin, dan jujur.
Anehnya, Chelsa nyaman.
Namun malam tetaplah malam.
Pukul 01.25, air mata Chelsa jatuh tanpa alasan.
Ia menangis dalam diam, ditemani suara malam yang muram.
Siang hari ia menjadi gadis ceria.
Malam hari ia hanyalah manusia lelah yang mencoba bertahan.
Ada saat-saat ketika pikirannya kehilangan arah.
Ia merasa hidupnya tidak meninggalkan jejak apa pun.
Namun di detik paling gelap itu, hatinya bergetar—
bukan karena takut mati,
melainkan karena takut kepergiannya tak berarti apa-apa.
Ia memilih bertahan.
Bukan karena hidup terasa indah,
tetapi karena ia menolak kalah.
Satu tahun kemudian.
Takdir mempertemukan mereka kembali.
Aura dan Chelsa sekelas lagi.
Tertawa lagi.
Diam bersama lagi.
Untuk pertama kalinya, Chelsa merasa dipahami tanpa perlu menjelaskan.
Diamnya tidak dihakimi.
Tangisnya tidak diremehkan.
“Ra, kalau gue nggak ada, lo bakal sedih nggak?”
“Ngaco.”
Chelsa tersenyum kecil.
Ia tak mengharapkan jawaban lain.
Namun luka tidak selalu pergi diam-diam.
Ia kembali—lebih sunyi, lebih licik.
Suara-suara di kepalanya berbisik:
“Kamu seharusnya sendiri.”
“Kehadiranmu hanya menyusahkan.”
Chelsa menangis lagi.
Bukan karena ia suka kesendirian,
melainkan karena ia terlalu lama memeluk luka tanpa pernah diajari cara melepaskannya.
Hingga suatu hari, ibunya berkata pelan,
“Mama tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Ayo ikut Mama.”
Chelsa harus pindah sekolah.
Keputusan itu pahit, tetapi perlu.
Ia tak mampu mengucapkan terima kasih.
Namun di dalam hatinya, ia menitipkan doa untuk Aura—
dan untuk semua manusia baik yang pernah singgah.
Chelsa akan terus hidup.
Bukan sebagai manusia batu.
Bukan pula sebagai topeng ceria.
Ia hanya ingin bernapas,
dan menjadi dirinya sendiri.
—————-
Di antara ratusan temu
dan kebetulan yang berujung semu
engkau adalah nyala yang membakar dari dalam
bukan karena singgahmu sebentar
tetapi karena hadirmu tak bisa ku namakan.
*) Karya Siswi Kelas 9 MTs Miftahul Ulum 2 Bakid