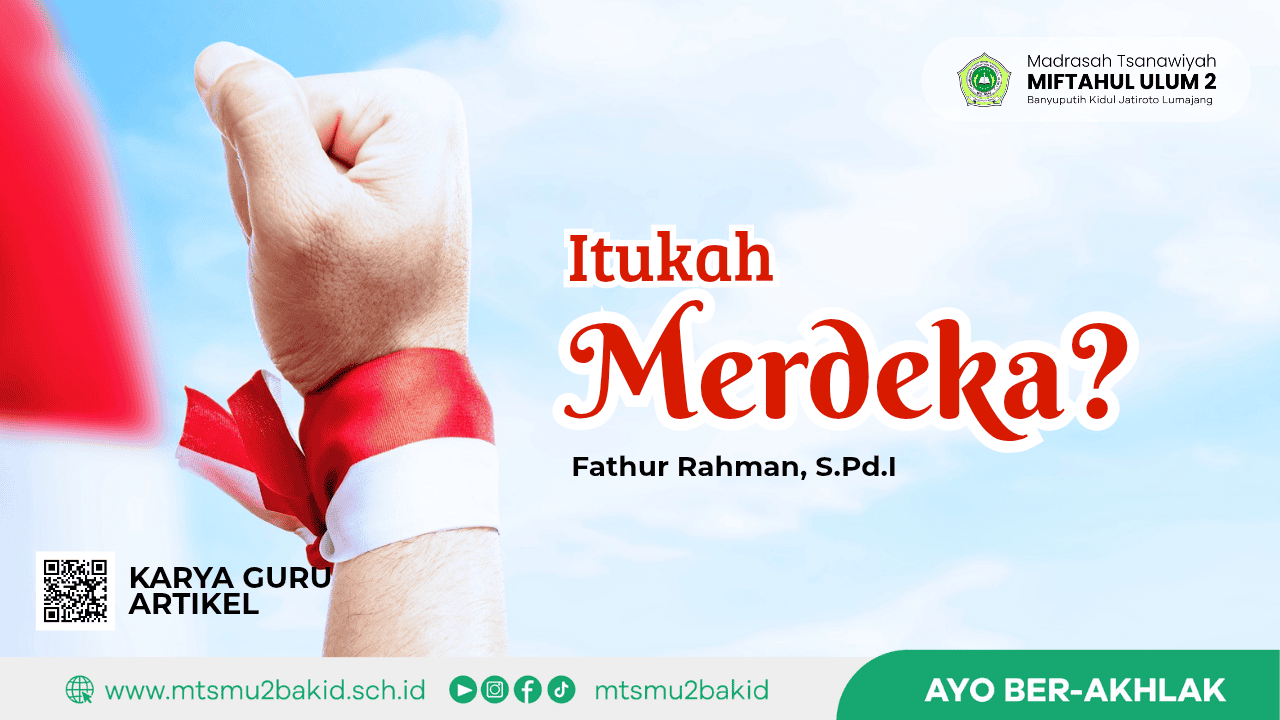Oleh: Fathur Rahman, S.Pd.I *)
Kokok ayam jantan mengakhiri keheningan malam.
Fajar pun di ufuk timur mulai menyingsing.
Kumandang adzan meramaikan toa-toa di langgar-langgar tua.
Embun pagi membasahi daun-daun kering,
dinginnya menembus kulit yang mulai keriput, hingga menusuk tulang.
Di atas tanah yang gersang,
aku, seorang buruh tani,
melangkah tanpa alas kaki,
berjuang mencari penghidupan untuk generasi anak negeri,
di negeri yang katanya Gemah Ripah Loh Jinawi.
Kulihat merah putih berkibar di tiang-tiang sepanjang jalan,
jalan-jalan yang penuh lubang dan bebatuan tak karuan.
Ooooh, ternyata…
negeriku tercinta, saatnya merayakan usianya.
Merdekaaa…
Sejak proklamasi itu dikumandangkan Sukarno-Hatta,
delapan puluh tahun sudah panji berkibar.
Merahnya darah pahlawan, putihnya niat yang suci.
Seremonial di istana, upacara di lapangan-lapangan,
pekik “Merdeka!” menggema dan membahana di seluruh pelosok negeri.
Mereka rayakan delapan dekade kemerdekaan,
dengan lagu dan tawa, dengan bendera dan hiasan, bahkan dengan jogetan.
Tapi di antara riuh tepuk tangan dan dentum meriam,
sebuah tanya menyelinap, tajam dan menikam
di lubuk hati anak bangsa yang paling dalam.
Sebuah bisik lirih memecah diam:
Itukah merdeka?
Siapa yang merdeka?
Bangsa ini, atau hanya para penguasa
yang hidup mewah bergelimang harta?
Siapa yang merdeka?
Rakyat yang dicekik upeti oleh penguasa,
atau mereka tikus-tikus berdasi
yang asyik menikmati empuknya kursi di Senayan sana?
Untuk siapa kemerdekaan itu?
Untuk kita rakyat jelata dan pengangguran yang bertebaran di mana-mana?
Ataukah untuk mereka para tersangka koruptor
yang mendapat ampunan bebas dari penguasa,
seakan tiada malu dan tanpa dosa?
Merdekaaa…!!! kata mereka.
Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Tema besutan penguasa,
seakan menggambarkan itulah Indonesia.
Namun siapa yang sejahtera?
Rakyat jelata, atau mereka para wakil rakyat yang melupakan pemilihnya?
Atau para pengusaha yang dipelihara penguasa?
Ataukah para penjilat yang berpelukan mesra dengan pengkhianat bangsa?
I
Lihatlah, Ibu Pertiwi, betapa molek dirimu.
Hamparan zamrud hutan di garis khatulistiwa,
emas, timah, dan tembaga terpendam dalam perut bumimu.
Lautan biru menyimpan mutiara dan kekayaan tak terkira.
Katanya, tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman.
Tapi mengapa di atas surga ini banyak rintih kelaparan?
Sumber daya alam kita diangkut kereta-kereta baja
menuju pelabuhan-pelabuhan megah yang asing namanya.
Gunung diratakan, hutan merana, sungai memerah luka—
atas nama pembangunan, atas nama devisa negara.
Harta pusaka dijarah, dirampok di siang hari
oleh mereka yang berjas rapi dan berdasi.
Anak cucu kita kelak mewarisi apa?
Cerita tentang kekayaan, atau lubang-lubang raksasa?
Itukah merdeka, jika tanah air tergadai?
Jika kekayaan bangsa hanya jadi tontonan di etalase ramai?
II
Di atas mimbar, mereka berpidato dengan lantang,
mengucap sumpah atas nama Tuhan dan Konstitusi.
Bicara tentang amanat penderitaan rakyat yang harus diemban,
menjanjikan keadilan, kemakmuran, dan negeri yang berseri.
Wajah mereka terpampang di baliho-baliho jalanan,
tersenyum manis, seolah tanpa beban.
Namun di balik senyum itu, tangan mereka lihai bermain,
menggoreskan tinta emas di atas kertas perjanjian.
Anggaran negara menjadi bancakan, proyek menjadi arisan.
Istana megah mereka dibangun di atas tangis dan penderitaan.
Perut mereka membuncit, sementara rakyat mengencangkan ikat pinggang.
Kursi mereka empuk, sementara rakyat tidur di lantai yang lekang.
Hukum?
Ia tajam menusuk ke bawah—pada sandal jepit yang hilang.
Namun tumpul di hadapan singgasana, di hadapan jubah kebesaran.
Keadilan menjadi barang langka, bisa dibeli dan ditimbang.
Itukah merdeka, jika para pemimpin menjadi perampok terhebat?
Jika suara rakyat hanya dibutuhkan saat lima tahun sekali berdebat?
III
Di gubuk-gubuk reot di pinggiran kota,
seorang ibu memasak nasi dengan air mata.
Anaknya bertanya:
“Ibu, kapan kita bisa makan daging rendang perayaan?”
Sang ibu hanya tersenyum getir, menelan ludah yang pahit rasanya.
Di sawah yang tak lagi miliknya, petani menatap nanar,
tanahnya telah menjadi beton atas nama investasi yang gencar.
Pagar-pagar laut pun dipasang,
nelayan melaut lebih jauh, menantang badai yang garang,
karena pesisir telah dikuasai para raksasa yang datang dari seberang.
Ajaibnya, para penguasa seakan bisu dan tuli dalam diam.
Kita kaya, kata mereka. Indonesia negara besar.
Tapi mengapa untuk sekolah, untuk sehat, terasa begitu sukar?
Generasi muda termangu di persimpangan jalan,
antara ijazah di tangan dan lapangan kerja yang hanya angan-angan.
Mereka hidup di atas permadani emas, namun tidur di lantai dingin.
Mereka menghirup udara kemerdekaan, namun jiwa mereka terkurung angin.
Itukah merdeka, jika sejahtera hanya milik segelintir manusia?
Jika mayoritas rakyat masih berjuang hanya untuk bertahan di esok hari?
Penutup
Delapan puluh tahun, sebuah angka yang agung,
bukan lagi usia muda untuk sebuah bangsa.
Namun jiwa kita terasa masih terpasung
oleh belenggu keserakahan dan ketidakpedulian penguasa.
Merdeka bukan sekadar pekik di lapangan dan halaman istana,
bukan hanya bendera yang melambai gagah di tiang tertinggi.
Merdeka adalah ketika keadilan menjadi panglima,
ketika setiap perut terisi, dan setiap mimpi punya ruang untuk meninggi.
Merdeka adalah ketika tak ada lagi tangis di lumbung padi,
dan para pemimpin benar-benar menjadi abdi.
Lihatlah kembali Sang Saka yang berkibar di angkasa.
Merahnya bukan lagi hanya lambang keberanian,
tapi juga darah dan air mata mereka yang terluka.
Putihnya bukan lagi hanya simbol kesucian,
tapi juga harapan tulus yang tak kunjung padam dari dada.
Di usianya yang ke delapan puluh, Indonesia bertanya dalam hening,
menatap wajah anak-anaknya yang letih, dan kening yang berkerut pening:
“Itukah merdeka?”
*) Pembina OSIM Putri MTs Miftahul Ulum 2 Bakid