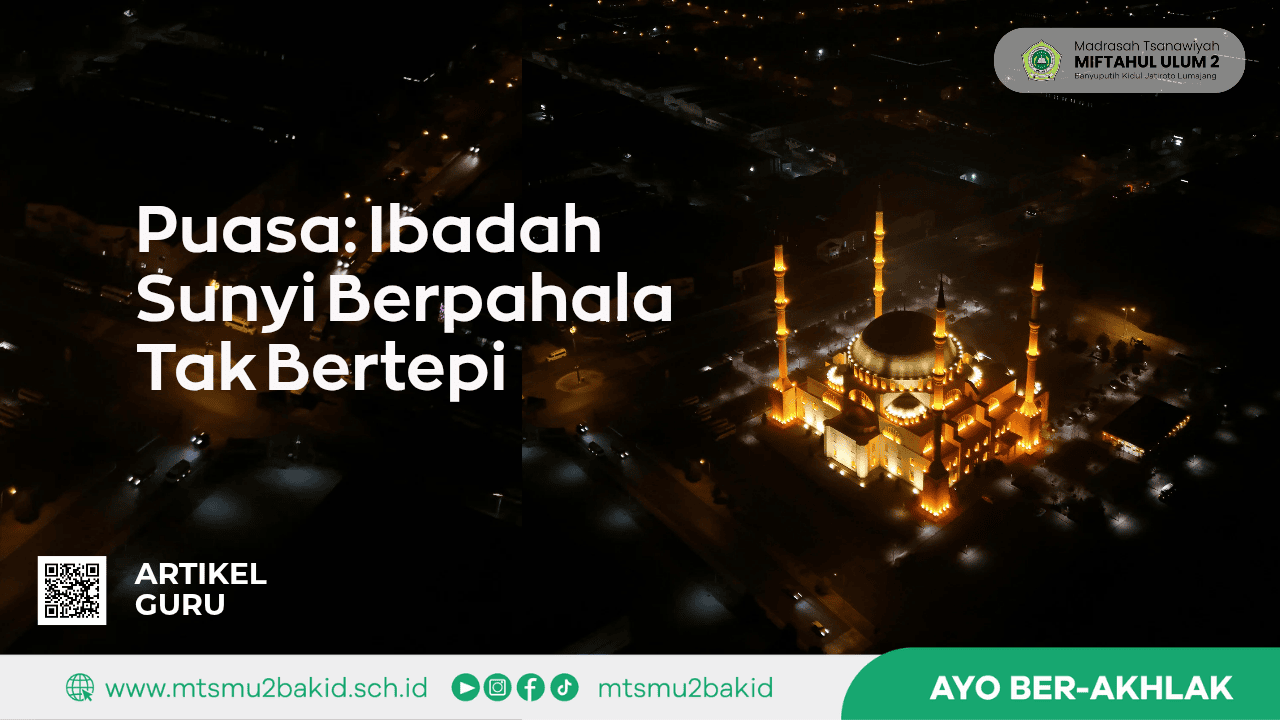Oleh: Muhammad Ridwansyah *)
Ayah dan Ibu mengumpulkan anak-anaknya di ruang tamu. Ada kabar penting yang ingin mereka sampaikan. Tak lama berselang, ketiga anak mereka sudah berkumpul, duduk rapi di depan kedua orang tuanya.
Ayah mulai bicara dengan penuh semangat, “Ada kabar gembira. Mulai hari ini kita akan pindah rumah!”
Semua terdiam. Termasuk Ibu yang terlihat terkejut.
“Pindah tugas, Pak?” tanya Ibu heran.
Ayah menggeleng pelan. “Ada orang yang menghibahkan rumahnya untuk kita tempati. Rumah itu di Kraeng Bella.”
“Rumah itu berhantu!” seru Romo spontan.
Mendengar itu, Ayah, Ibrahim, dan Kulle hanya tersenyum kecil.
“Tapi… aku tidak takut hantu!” ucap Romo tegas.
“Betul,” kata Ayah. “Itu sebabnya Ayah setuju kita pindah ke sana.”
Ibu masih tampak ragu. “Bagaimana kalau suatu saat Pak Suhaimi, pemilik rumah itu, ingin menempatinya kembali?”
“Beliau tidak akan kembali ke rumah itu,” jelas Ayah. “Rumah itu sudah dipercayakan pada kita, asal tidak dijual.”
Ibrahim tertawa mendengar syarat itu. “Jangan dijual, Ayah. Itu kan memang bukan rumah kita.”
Ayah mengangguk. “Benar. Hak kita hanya menempati. Mulai besok, kita pindah. Malam ini, segera tidur. Besok pagi kita mulai angkut barang-barang.”
Semua pun berdiri dan bersiap kembali ke kamar masing-masing. Kecuali Ibrahim. Ia masih bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya, memegang selembar kertas.
“Ada apa, Nak?” tanya Ibu pelan.
Ibrahim menelan ludah, diam, lalu menyodorkan selembar surat keterangan persetujuan orang tua kepada Ayah. Dengan penuh tanda tanya, Ayah meraih surat itu dan membacanya. Matanya membelalak.
“Kamu mau masuk Akademi Militer?”
Ibrahim mengangguk.
“Uang dari mana, Nak?” sergah Ayah, nadanya mulai meninggi. “Ayah tidak masalah kamu mau jadi apa, asal masuk akal. Gaji Ayah sebagai kepala sekolah dasar tak seberapa. Kamu tahu itu.”
Ibrahim tetap diam.
Ayah semakin marah. “Kamu minta Ayah tanda tangan di sini? Kamu pikir semua ini murah?”
Ibu mencoba menenangkan. “Tenang, Pak. Biarkan Leo bicara dulu.”
Sambil menunduk, Ibrahim berkata lirih, “Tidak dipungut biaya sepeser pun, Ayah. Semua biaya ditanggung negara.”
Ayah tertawa sinis. “Itu di atas kertas, Nak. Fakta di lapangan sering jauh berbeda.”
“Itu yang ingin Leo buktikan, Pak. Leo ingin lulus karena kemampuan, bukan karena uang.”
Ayah menggeleng, suaranya datar. “Kalau begitu, Ayah tidak bisa menandatangani. Maaf, Nak. Ayah tidak akan setuju dengan sesuatu yang Ayah ragukan.”
Ibrahim mengangguk pelan. Ia tahu, keputusan Ayah sudah bulat. Tak ada bujukan yang bisa mengubahnya. Dengan hati berat, ia mengambil kembali surat itu dan beranjak ke kamar.
Ayah hanya menggeleng pelan, tak habis pikir melihat tekad anaknya.
Di kamar, Kulle sudah menunggunya.
“Mana surat izinnya?” tanya kakaknya.
Ibrahim menyodorkannya.
Tanpa berkata apa-apa, Kulle langsung menandatanganinya dengan tanda tangan yang sangat mirip milik Ayah.
Ibrahim diam. Ia sempat pasrah, tapi kini semangatnya menyala lagi. Ia tahu, yang dilakukannya bukan untuk menentang Ayah, tapi demi masa depan.
“Jangan menyerah,” kata Kulle. “Anggap ini batu sandungan pertama.”
“Iya, Kak.”
“Sekarang tidurlah. Besok hari penting.”
Semua penghuni rumah tertidur lelap. Kecuali Ibrahim. Ia duduk di meja belajarnya, menulis surat dengan tangan gemetar. Di hadapannya, sebuah tas penuh berisi pakaian. Ia sudah membulatkan tekad untuk pergi — bukan melarikan diri, hanya sementara, selama empat tahun.
Ia ingin kembali sebagai kebanggaan keluarga.
Air matanya menetes saat menulis. Berkali-kali ia pernah berpisah dengan orang tua, tapi kali ini rasanya berbeda. Perpisahan yang sesungguhnya. Surat itu ia letakkan di meja tempat Ayah biasa duduk pagi hari sambil menikmati kopi.
Ia berdiri, mengangkat tas, dan melangkah ke pintu kamarnya.
Kulle dan Romo masih tertidur. Ia menatap mereka penuh haru.
“Jaga Bapak dan Ibu, Kak Kulle…”
Sulit rasanya meninggalkan orang-orang yang ia sayangi. Tapi ada impian besar yang harus dikejar.
Ia menoleh ke Romo dan berbisik, “Jaga mereka, ya.”
Sesak di dadanya kian terasa. Tapi ia tidak boleh mundur.
“Aku menyayangi kalian… sepenuh hati.”
Ia menarik napas panjang, membalikkan badan, lalu melangkah perlahan ke ruang tamu tanpa menoleh lagi.
Adzan Subuh baru saja berkumandang.
_______
Langkah kaki Ibrahim menyusuri jalan kampung yang masih gelap dan sunyi. Dengan tas besar di pundak dan tekad yang penuh di dada, ia melangkah pasti menuju stasiun. Hatinya masih berat, bukan karena ragu, tapi karena harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya tanpa restu penuh dari sang Ayah.
Empat tahun pun berlalu.
Hari itu matahari bersinar cerah di atas rumah tua mereka di Kraeng Bella. Di teras rumah, Ayah duduk dengan secangkir kopi seperti biasa, menatap halaman yang mulai ramai. Warga desa berbisik-bisik, banyak yang berjalan ke lapangan dekat rumah karena katanya akan ada upacara penyambutan taruna lulusan terbaik dari Akademi Militer yang berasal dari desa mereka.
Ayah hanya menghela napas, seakan tak tertarik. Ia merasa tersentil tiap kali mendengar nama Ibrahim disebut-sebut oleh warga desa. Tapi entah kenapa pagi itu, ia merasa gelisah, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sejak Ibrahim pergi empat tahun lalu, surat demi surat ia terima, namun tak satu pun ia balas. Ia baca diam-diam, menyimpannya rapi di laci meja ruang tamu.
Ibu keluar dari dapur sambil tersenyum. “Pak, ayo kita ke lapangan. Katanya Ibrahim datang hari ini.”
Ayah mengerutkan kening. “Biar saja, Bu. Dia sudah pilih jalannya sendiri.”
“Tapi dia tetap anak kita, Pak. Meski jalannya berbeda dari yang kita harapkan, bukankah dia tetap berjuang dengan jujur dan keras?”
Ayah terdiam.
Tak lama kemudian, terdengar suara barisan pasukan berseragam yang masuk ke halaman desa. Semua mata tertuju pada barisan itu. Di depan, seorang pemuda tegap berseragam taruna penuh kebanggaan membawa bendera merah putih dengan gagah. Di pundaknya tersampir selempang “Lulusan Terbaik Nasional – AMN”.
Itu Ibrahim.
Ayah tertegun. Napasnya tercekat. Sosok anak yang dulu berangkat dengan diam-diam kini berdiri tegak, disambut sorak sorai masyarakat desa. Semua mata memandang penuh kagum.
Ibrahim melangkah mendekat ke arah kedua orang tuanya. Ia menghormat di depan Ayah dan Ibu, lalu bersimpuh dan mencium tangan keduanya.
Ayah menahan air mata.
“Maafkan Leo, Ayah. Maaf karena Leo memilih jalan ini tanpa izinmu. Tapi semua ini… untuk membuat Ayah bangga.”
Ayah tak mampu berkata-kata. Tangannya bergetar saat mengangkat dagu Ibrahim, memandang matanya yang jernih dan berani.
“Leo… Ayah yang harusnya minta maaf. Kamu membuktikan segalanya dengan kerja keras. Kamu anak Ayah… anak yang Ayah banggakan.”
Ayah memeluk Ibrahim erat. Tangisnya pecah.
Ibu ikut menangis haru. Kulle dan Romo berlari menyambut kakaknya. Warga desa bertepuk tangan meriah menyambut pahlawan muda dari desa mereka.
Sejak hari itu, hubungan Ibrahim dan Ayah semakin dekat. Mereka sering duduk bersama, berbincang tentang mimpi, perjuangan, dan masa depan. Ayah kini selalu menyisipkan satu nasihat penting kepada para tetangga:
“Jangan pernah ragukan mimpi anakmu, selama dia memperjuangkannya dengan jujur dan sungguh-sungguh.”
TAMAT.
*) Siswa Kelas 8 MTs Miftahul Ulum 2 Bakid